Penulis : Yunan Isra
Membaca pesantren dalam paradigma modernis merupakan sebuah kajian yang sangat urgen sekaligus menarik. Karena, kita bisa mengetahui sejauh mana gaung pesantren dalam menghadapi cakrawala kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Hal itu juga bisa dihadapkan dengan kritikan-kritikan yang muncul terhadap pesantren. Kritikan berupa kredibilitasnya sebagai sebuah lembaga pendidikan tradisional Nusantara dalam menghadapi kemajuan teknologi dan merespon persoalan-persoalan kontemporer yang jamak bermunculan serta harus segera dicarikan solusinya itu.
Pesantren sebagai lembaga tradisional Islam, dengan meminjam pemetaan Sayyed Hossein Nasr, merupakan sebuah lembaga yang dikembangkan dan diwarisi secara turun-temurun oleh para ulama tradisional Islam semenjak beberapa tahun yang lalu. Substansinya tidak jauh berbeda dengan keberadaan kaum Salaf pada abad-abad pertama perkembangan agama Islam itu sendiri, yaitu periode para Sahabat Nabi Muhammad dan Tabi’in senior. Bahkan pesantren telah ada sejak pada masa kekuasaan Hindu-Buddha, sebagaimana yang dijelaskan oleh Cak Nur pada bagian awal dari buku Bilik-bilik Pesantren-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pesantren bukanlah anak kemarin sore yang tidak mempunyai andil ataupun pengalaman sedikitpun dalam membina kehidupan masyarakat Indonesia.
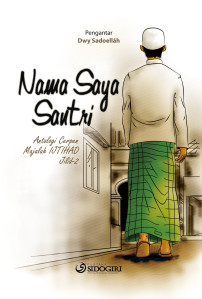 Ditilik dari tujuan dasarnya, pesantren adalah produsen terpenting dalam mempertahankan transmisi dan transfer ilmu-ilmu keislaman, sekaligus sebagai badan pengawas jalannya kontinuitas tradisi Islam serta reproduksi para ulama yang tafaqquh fiddin dengan menjadikan al-Qur’an dan Hadis sebagai objek kajiannya. Itulah sekurang-kurangnya tiga misi utama yang diemban dan diperjuangkan oleh lembaga ini. Di sisi lain, tidak sedikit alumnus-alumnus pondok pesantren yang mempunyai pengaruh penting dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan republik ini di tahun 1945 yang silam. Tapi sayangnya peranan-peranan itu dianggap sebagai angin lalu yang tidak perlu diapresiasi sedikitpun oleh sebagian golongan, terutama bagi kalangan modernis.
Ditilik dari tujuan dasarnya, pesantren adalah produsen terpenting dalam mempertahankan transmisi dan transfer ilmu-ilmu keislaman, sekaligus sebagai badan pengawas jalannya kontinuitas tradisi Islam serta reproduksi para ulama yang tafaqquh fiddin dengan menjadikan al-Qur’an dan Hadis sebagai objek kajiannya. Itulah sekurang-kurangnya tiga misi utama yang diemban dan diperjuangkan oleh lembaga ini. Di sisi lain, tidak sedikit alumnus-alumnus pondok pesantren yang mempunyai pengaruh penting dalam usaha mempersiapkan kemerdekaan republik ini di tahun 1945 yang silam. Tapi sayangnya peranan-peranan itu dianggap sebagai angin lalu yang tidak perlu diapresiasi sedikitpun oleh sebagian golongan, terutama bagi kalangan modernis.
Berbagai kritikan keras dan opini negatif pada saat ini, tengah dihadapi oleh pesantren. Khususnya dari kalangan modernis yang notabenenya berlatarbelakang sistem pendidikan Belanda atau lebih sering disebut dengan sistem pendidikan sekular (Barat). Mereka tak henti-hentinya mengupas sisi-sisi buruk pesantren serta menganggap keberadaan pesantren di era globalisasi saat ini sudah saatnya direkontruksi ataupun bahkan didekontruksi sama sekali dari sistem pendidikan nasional. Karena dianggap dapat mengantarkan umat manusia kepada pintu gerbang kejumudan dan keterbelakangan. Azyumardi Azra menukil seperti berikut :
“Bagi para eksponen sistem pendidikan Belanda, seperti Sutan Takdir Alisyahbana, pesantren harus ditinggalkan atau setidaknya ditransformasikan sehingga mampu mengantarkan kaum Muslim ke gerbang rasionalitas dan kemajuan. Jika pesantren dipertahankan, menurut Takdir, berarti mempertahankan keterbelakangan dan kejumudan kaum Muslim”

Tidak begitu berbeda dengan Sutan Takdir, dalam bukunya Bilik-bilik Pesantren, Dr. Nurcholish Madjid, juga melontarkan sebuah sentilan kecil terhadap pesantren, yaitu :
“Kurangnya kemampuan pesantren dalam meresponi dan mengimbangi perkembangan zaman tersebut, ditambah dengan faktor lain yang sangat beragam, membuat produk-produk pesantren dianggap kurang siap untuk “lebur” dan mewarnai kehidupan modern.”
Dan masih banyak lagi sisi-sisi negatif pesantren yang dipandang oleh kalangan modernis semisal Sutan Takdir Alisyahbana, Nurcholish Madjid, dan lain-lain, sebagai sebuah aib ataupun kecacatan yang sudah sepatutnya didekontruksi demi mengantarkan Islam menuju kemajuan dan bangkit dari keterpurukan sebagaimana yang akan dijelaskan berikut ini.
Riwayat Hidup Cak Nur
Sebagai seorang yang berlatarbelakang pesantren, pemikir yang akrab dipanggil dengan Cak Nur ini, bukanlah orang yang buta dengan dunia pesantren. Dalam biografinya yang ditulis oleh Faisal Ismail disebutkan bahwa Cak Nur berhasil menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren Darul U’lum, Rejoso, Jombang, Jawa Timur, pada tahun 1955 dan melanjutkannya ke Pondok Modern Gontor yang terletak di daerah Ponorogo, Jawa Tengah, pada tahun 1960. Di pondok inilah dia secara kuat membangun fondasi dan basis intelektualnya sehingga dapat menguasai bahasa Arab dan Inggris dengan baik.
Setelah itu, dia melanjutkan studinya ke Fakultas Adab/Sastra dan Budaya IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN) Jakarta dan tamat pada tahun 1965 dengan menggondol predikat sarjana muda (BA) dan predikat Doktorandus pada tahun 1968. Basis, bobot, dan intelektual Cak Nur menjadi jauh lebih terasah tajam ketika dia melanjutkan studinya ke program doktor Universitas Chicago Amerika Serikat dan selesai pada tahun 1984. Itulah sedikit mengenai riwayat pendidikan dari seorang santri yang kemudian bermutasi menjadi seorang pemikir ulung Nusantara itu. Dia juga semasa dengan pemikir Nusantara lainnya yang terkenal dengan sapaan Gus Dur, cucu dari K.H. Hasyim Asy’ari, pendiri organisasi Nahdhatul Ulama.
Dilihat dari sejarah pendidikannya tersebut, sangat wajarlah kiranya kalau Cak Nur berkomentar mengenai pesantren. Pengalaman beberapa tahun mondok di dua pesantren yang berbeda dari segi orientasi itu, cukup menjadi bekal dan bahan hipotesis baginya dalam menilai pesantren. Namun untuk menguji kebenaran kritikannya terhadap pesantren, diperlukan adanya sebuah komparasi ataupun peninjauan kembali mengenai sejauh mana kesinkronan kritikan tersebut dengan realitas yang ada di lapangan.

Cak Nur dan Pandangannya terhadap Pesantren
“DARI SEGI HISTORIS PESANTREN TIDAK HANYA IDENTIK DENGAN MAKNA KEISLAMAN, TETAPI JUGA MENGANDUNG MAKNA KEASLIAN INDONESIA (INDIGENOUS).” –DR. NURCHOLISH MADJID.
Untuk mengetahui pandangan-pandangannya mengenai pesantren, maka buku Bilik-bilik Pesantren adalah buku yang cukup representatif untuk itu. Buku yang pada awalnya hanyalah percikan pikiran Cak Nur mengenai pesantren yang tersebar di berbagai media, kemudian dibukukan oleh penerbit Paramadina dengan judul seperti di atas.
Banyak hal menarik dalam buku tersebut yang perlu kiranya ditanggapi secara kritis oleh kaum pesantren. Pada bab pertama misalnya, Cak Nur mencoba untuk merumuskan kembali tujuan pendidikan pesantren yang menurut dia sudah semestinya mendapat perhatian lebih. Di satu sisi dia mengharapkan pesantren-pesantren yang ada, dapat mempertahankan tradisi-tradisi keagamaan yang dimilikinya, karena di sanalah letak kelebihannya. Namun di sisi lain, Cak Nur seolah-olah bersikap pesimis dan cenderung “menghantam” sistem pesantren yang “mustahil” bisa menyeimbangi sistem-sistem Barat yang begitu sempurna dalam pandangannya. Misalnya saja ketika dia mengapresiasi institusi Harvard sebagai institusi keagamaan yang telah berhasil memegang kepeloporan dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern dan gagasan-gagasan mutakhir di Amerika Serikat. Begitu juga terhadap keberhasilannya memproduksi orang-orang besar yang menduduki kekuasaan tertinggi di negara adikuasa tersebut.
Kemudian dia juga mengkritik pesantren dari segi kurikulumnya yang tidak memberi lahan terhadap pengembangan ilmu-ilmu kesosialan. Hal ini ditandai dengan minimnya mata pelajaran umum yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Padahal hal itu sangat urgen dalam menyokong keterampilan santri dalam mengatur masyarakat yang nantinya menjadi lahan praktiknya. Hal itu terbukti dari mata pelajaran yang diajarkan di pesantren seperti ilmu Nahu, Sharaf, Fikih, Akidah, Tasawuf, Tafsir, Hadis, dan Bahasa Arab. Tidak satupun dari mata pelajaran itu yang mengandung nilai sosial. Dalam hal ini Cak Nur mengatakan perlunya pesantren mengubah orientasinya untuk membentuk manusia yang memiliki kesadaran tinggi bahwa ajaran Islam merupakan weltanschauung yang bersifat menyeluruh.
Selanjutnya, di bagian kedua dari buku tersebut, Cak Nur juga mengomentari pola pergaulan dalam pesantren dan menganalisa unsur-unsur pembentuk dari pesantren itu sendiri seperti asal-usul istilah santri, kiai, ngaji, dan lain-lain. Dia menyoroti sistem pengajaran pesantren yang terlalu mengedepankan keortodoksian, sehingga terkesan mengenyampingkan optimalisasi waktu dan bahan ajar. Dia berkata seperti berikut :
“Karena sistem pengajian yang harus menerjemahkan terlebih dahulu itu, maka tidak mengherankan bahwa proses memahami dan menamatkan sebuah kitab begitu sulit dan panjang bagi seorang santri. Tidak jarang seorang santri yang telah mondok bertahun-tahun, pulang hanya membawa keahlian “mengaji” beberapa kitab saja.”
Hal senada juga pernah dilontarkan oleh Muhammad Thalhah Hasan, salah seorang intelektual muslim kalangan Nahdhatul Ulama (NU) yang pernah mengkritik bahwa tradisi pengajaran pesantren yang seperti itu memberikan dampak lemahnya kreativitas. Dan kalau yang mendapatkan penekanan di pesantren itu adalah ilmu fikih (fikih oriented), maka penerapan fikih menjadi teralienasi dengan realitas sosial dan keilmuan serta teknologi kontemporer. Namun sebaliknya dalam pandangan antropolog Zamakhsyari Dhofier, alumnus Jurusan Antropologi, Universitas Nasional Australia, pesantren memainkan peranan sangat penting dan signifikan dalam memelihara dan melestarikan paham-paham keislaman tradisional.
Tak ketinggalan relasi pesantren dengan dunia politik juga menjadi salah satu bahan soroton Cak Nur. Menurut dia keterkaitan antara pesantren dengan politik dapat dipahami dengan melihat kedudukan pesantren sebagai trustee masyarakat santri, dimana para santri ini mengharapkan bimbingan kultural, khususnya dalam hubungannya dengan agama Islam. Namun ideologi santri harus dibedakan dari agama Islam itu sendiri tegasnya, karena kekhususan sifat dan corak keislaman kaum santri telah banyak mendapatkan warna lokal yaitu kejawaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pesantren merupakan salah satu tempat dilahirkannya suatu aliran ideologi politik tertentu di Indonesia dengan pembelaan yang jelas dan tertentu pula, baik yang positif maupun yang negatif.
Selain poin-poin di atas, sebenarnya masih banyak wacana-wacana seputar pesantren yang digulirkan oleh Cak Nur dalam bukunya tersebut. Hanya saja tidak penulis cantumkan ke dalam tulisan ini lantaran ketidaksinkronannya terhadap realitas pesantren yang ada pada saat ini. Hal ini mungkin bisa dimaklumi mengingat tulisan-tulisan Cak Nur tersebut ditulis sekitar tahun 1970-an yang kemudian baru terkumpul menjadi sebuah buku utuh pada tahun 1997 silam. Seperti kritikannya terhadap kondisi fisik pesantren yang terkesan kumuh dengan “tata kota” yang terkesan sporadis, jumlah kamar mandinya yang tidak sebanding dengan jumlah santrinya, kebersihan yang kurang terjaga sehingga menyebabkan timbulnya berbagai penyakit yang menimpa para santri. Begitu juga dengan sistem kepemimpinan pesantren yang tersentralisasi di sang kiai sebagai satu-satunya pemegang kendali maju atau mundurnya sebuah pesantren. Hal ini menurut Cak Nur menjadi salah satu sebab pokok tertinggalnya pesantren dari perkembangan zaman.













